Paham Komunis dan Hukum Keluarga: Perspektif Ideologi, Implementasi, dan Relevansi di Indonesia
romanticheadlines.com, 28 MEI 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88
Paham komunis, yang berakar pada teori Karl Marx dan Friedrich Engels, adalah ideologi sosial, politik, dan ekonomi yang bertujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas melalui penghapusan kepemilikan pribadi dan penguasaan kolektif atas alat produksi. Dalam konteks hukum keluarga (family law), komunisme mengusulkan pendekatan radikal yang menentang struktur keluarga tradisional, yang dianggap memperkuat ketimpangan kapitalis. Hukum keluarga dalam komunisme berfokus pada kesetaraan gender, kolektivisasi tanggung jawab rumah tangga, dan pelemahan ikatan keluarga sebagai unit ekonomi. Artikel ini mengeksplorasi secara mendalam prinsip hukum keluarga dalam paham komunis, implementasinya di negara-negara komunis, dampaknya, serta konteksnya di Indonesia, di mana ideologi ini dilarang. Dengan memadukan perspektif ideologis, historis, dan hukum, artikel ini juga membandingkan pendekatan komunis dengan hukum keluarga Indonesia yang berbasis UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pengertian Hukum Keluarga dan Paham Komunis
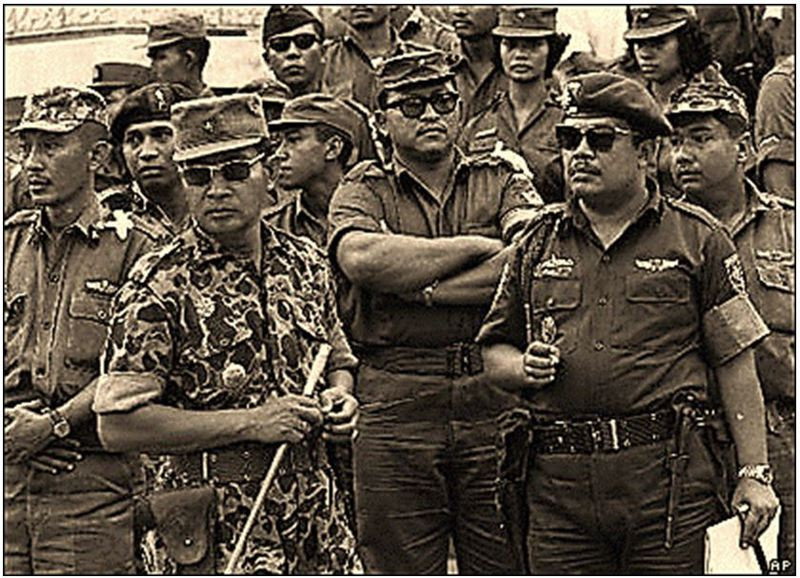
Hukum Keluarga (Family Law)
Menurut Hukumonline.com, hukum keluarga adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan hukum berdasarkan ikatan kekerabatan, baik melalui darah (misalnya, hubungan orang tua-anak) maupun perkawinan (hubungan suami-istri). Bidang utama hukum keluarga meliputi:
- Perkawinan: Aturan tentang syarat, pelaksanaan, dan pembubaran perkawinan, termasuk harta bersama.
- Kekuasaan Orang Tua: Hubungan hukum antara orang tua dan anak, termasuk pengasuhan dan tanggung jawab.
- Perwalian dan Pengampuan: Perlindungan bagi anak atau individu yang tidak mampu mengurus kepentingannya.
- Warisan: Pengalihan harta setelah kematian, yang sering tumpang tindih dengan hukum harta benda.
Di Indonesia, hukum keluarga diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengedepankan asas monogi dan konsensus, serta dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan dan adat. Hukum waris, meskipun terkait, memiliki posisi khusus karena melibatkan hukum harta benda.
Paham Komunis

Komunisme, sebagaimana diuraikan dalam Manifesto Komunis (1848), mengusulkan penghapusan kepemilikan pribadi dan pembentukan masyarakat tanpa kelas, di mana alat produksi dikuasai secara kolektif. Menurut Marx dan Engels, institusi keluarga dalam masyarakat kapitalis mempertahankan ketimpangan dengan:
- Menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga, mencerminkan dominasi borjuis.
- Menjadikan perempuan sebagai “alat produksi” domestik, terikat pada peran rumah tangga.
- Memperkuat pewarisan kekayaan, yang memperpetuasi kesenjangan kelas.
Dalam The Origin of the Family, Private Property, and the State (1884), Engels berargumen bahwa keluarga monogami muncul seiring kepemilikan pribadi untuk memastikan pewarisan harta kepada keturunan sah. Komunisme bertujuan “membebaskan” keluarga dari fungsi ekonomi ini dengan menggantinya dengan struktur komunal yang egaliter.
Prinsip Hukum Keluarga dalam Paham Komunis

Dalam ideologi komunis, hukum keluarga dirancang untuk mendukung tujuan masyarakat tanpa kelas. Berdasarkan teori Marx dan Engels, prinsip utama meliputi:
- Kesetaraan Gender:
- Perempuan dibebaskan dari subordinasi domestik melalui akses setara ke pekerjaan dan pendidikan.
- Perkawinan didasarkan pada cinta bebas (free love), bukan kepentingan ekonomi atau patriarki.
- Tanggung jawab rumah tangga, seperti pengasuhan anak, dikolektifkan melalui fasilitas negara, seperti penitipan anak.
- Penghapusan Harta Pribadi:
- Harta perkawinan tidak diakui sebagai milik individu, karena kepemilikan dialihkan ke kolektif.
- Warisan dihuela untuk mencegah akumulasi kekayaan antargenerasi.
- Kolektivisasi Pengasuhan:
- Anak-anak dianggap tanggung jawab masyarakat, bukan keluarga.
- Pendidikan dan pengasuhan disediakan oleh negara untuk memastikan kesetaraan akses.
- Pelemahan Ikatan Keluarga Tradisional:
- Keluarga sebagai unit ekonomi digantikan oleh komunitas kolektif.
- Loyalitas individu dialihkan dari keluarga ke negara atau kolektif.
Prinsip ini bertujuan menciptakan masyarakat egaliter, tetapi implementasinya bervariasi di negara-negara komunis, dipengaruhi oleh budaya lokal dan kebijakan politik.
Implementasi Hukum Keluarga di Negara Komunis
Uni Soviet (1917–1991)

Setelah Revolusi Bolshevik 1917, Uni Soviet menerapkan reformasi hukum keluarga radikal berdasarkan ideologi komunis:
- Kode Keluarga 1918:
- Perkawinan disederhanakan menjadi kontrak sipil, tanpa upacara agama.
- Perceraian dipermudah tanpa memerlukan alasan, mendukungkan kesetaraan gender.
- Harta perkawinan dianggap milik bersama, tetapi dikontrol negara.
- Kolektivisasi: Penitipan anak dan kantin komunal dibentuk untuk membebaskan perempuan dari tugas domestik.
- Warisan: Pada 1920-an, warisan pribadi dihapus, meskipun dikembalikan sebagian pada 1940-an karena resistensi sosial.
- Pendidikan: Anak-anak dididik di sekolah negara untuk menanamkan ideologi komunis, mengurangi pengaruh keluarga.
Namun, reformasi ini menghadapi tantangan:
- Resistensi Budaya: Banyak masyarakat Rusia yang konservatif menolak perkawinan bebas dan kolektivisasi.
- Krisis Sosial: Perceraian massal dan anak terlantar meningkat pada 1920-an, memaksa Stalin memperketat kebijakan keluarga pada 1930-an.
- Kontrol Negara: Alih-alih membebaskan, negara mengambil alih peran patriarki, mengontrol perkawinan dan pengasuhan.
Republik Rakyat Tiongkok (1949–Sekarang)

Setelah berdirinya RRC pada 1949, Mao Zedong menerapkan hukum keluarga berdasarkan komunisme:
- UU Perkawinan 1950:
- Menghapus perkawinan paksa dan poligami, menegakkan asas monogami dan persetujuan bebas.
- Perempuan diberi hak setara dalam perkawinan, perceraian, dan kepemilikan harta.
- Komune Rakyat: Pada era Great Leap Forward (1958–1962), komune mengelola pengasuhan anak dan kebutuhan rumah tangga.
- Warisan: Harta pribadi dibatasi, dengan fokus pada kepemilikan kolektif.
Tantangan:
- Resistensi Pedesaan: Budaya patriarki di pedesaan menghambat kesetaraan gender.
- Kebijakan Satu Anak (1979–2015): Meskipun bukan bagian langsung dari hukum keluarga komunis, kebijakan ini membatasi otonomi keluarga demi kontrol populasi.
- Perubahan Pasca-Mao: Reformasi ekonomi Deng Xiaoping pada 1980-an mengembalikan beberapa aspek kepemilikan pribadi, melemahkan pendekatan komunis murni.
Kuba (1959–Sekarang)
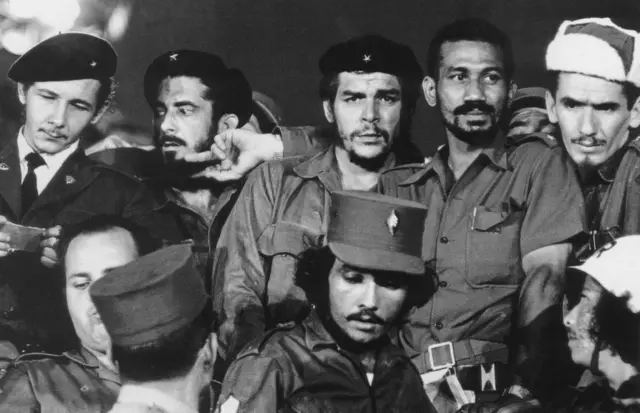
Kuba di bawah Fidel Castro menerapkan hukum keluarga yang mencerminkan komunisme dengan nuansa lokal:
- Kode Keluarga 1975:
- Menegakkan kesetaraan gender dalam perkawinan dan tanggung jawab rumah tangga.
- Mendorong partisipasi perempuan dalam angkatan kerja melalui fasilitas penitipan anak.
- Pendidikan: Sistem pendidikan negara mengurangi peran keluarga dalam pembentukan ideologi anak.
- Warisan: Kepemilikan pribadi dibatasi, dengan harta dialihkan ke kolektif atau negara.
Kuba berhasil meningkatkan kesetaraan gender, tetapi keterbatasan ekonomi menghambat kolektivisasi penuh, dan keluarga tetap menjadi unit sosial penting.
Perbandingan dengan Hukum Keluarga di Indonesia
Hukum keluarga di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sangat berbeda dari pendekatan komunis karena berakar pada nilai-nilai Pancasila, agama, dan adat. Berikut perbandingan utama:
- Dasar Ideologi:
- Komunis: Menolak agama dan tradisi, mengutamakan kolektivisme dan kesetaraan kelas. Keluarga dianggap institusi kapitalis yang harus dilemahkan.
- Indonesia: Berbasis Ketuhanan Yang Maha Esa, mengakui peran agama (Islam, Kristen, Hindu, dll.) dan adat dalam perkawinan. Keluarga adalah unit dasar masyarakat yang harus dilindungi.
- Perkawinan:
- Komunis: Perkawinan adalah kontrak sipil berbasis cinta bebas, tanpa ikatan agama atau ekonomi. Perceraian dipermudah untuk mendukung otonomi individu.
- Indonesia: Perkawinan adalah “ikatan lahir batin” untuk membentuk keluarga bahagia, dengan asas monogami dan konsensus (Pasal 1 dan 6 UU No. 1/1974). Perceraian diatur ketat, terutama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Harta Perkawinan:
- Komunis: Harta perkawinan dihapus atau dikolektifkan, karena kepemilikan pribadi ditolak.
- Indonesia: Harta bersama diakui (Pasal 35 UU No. 1/1974), dengan pengaturan berdasarkan agama atau perjanjian perkawinan.
- Warisan:
- Komunis: Warisan dihuela untuk mencegah akumulasi kekayaan, dengan harta dialihkan ke negara atau kolektif.
- Indonesia: Warisan diatur berdasarkan hukum agama (misalnya, faraid dalam Islam) atau adat, dengan keluarga sebagai ahli waris utama. Hukum waris terkait erat dengan hukum keluarga, tetapi juga hukum harta benda.
- Pengasuhan Anak:
- Komunis: Pengasuhan dikolektifkan melalui fasilitas negara, mengurangi peran keluarga.
- Indonesia: Orang tua memiliki kekuasaan utama atas anak (Pasal 45 UU No. 1/1974), dengan perwalian jika diperlukan.
- Kesetaraan Gender:
- Komunis: Menekankan kesetaraan penuh, dengan perempuan didorong bekerja dan terlibat dalam kolektif.
- Indonesia: Mengakui kesetaraan dalam rumah tangga (Pasal 31 UU No. 1/1974), tetapi peran gender sering dipengaruhi oleh norma agama dan adat, yang kadang mempertahankan elemen patriarki.
Dampak Hukum Keluarga Komunis
Dampak Positif
- Kesetaraan Gender: Reformasi di Uni Soviet, Tiongkok, dan Kuba meningkatkan akses perempuan ke pendidikan dan pekerjaan, mengurangi ketergantungan pada laki-laki.
- Akses Pendidikan: Kolektivisasi pengasuhan memungkinkan anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan.
- Pengurangan Poligami: Penegakan monogami di Tiongkok menghapus praktik poligami yang merugikan perempuan.
Dampak Negatif
- Krisis Sosial: Di Uni Soviet, perceraian massal dan anak terlantar meningkat pada 1920-an akibat kebijakan perkawinan bebas.
- Resistensi Budaya: Pendekatan komunis sering bertentangan dengan nilai-nilai tradisional, menyebabkan penolakan masyarakat.
- Kontrol Negara: Alih-alih membebaskan, negara komunis sering mengambil alih peran patriarki, membatasi otonomi individu.
- Keterbatasan Ekonomi: Kolektivisasi penuh sulit diterapkan di negara-negara dengan sumber daya terbatas, seperti Kuba.
Konteks Komunisme di Indonesia
Di Indonesia, komunisme memiliki sejarah kontroversial, terutama terkait Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dibubarkan setelah peristiwa G30S 1965. Berdasarkan UU No. 27 Tahun 1999 dan TAP MPRS No. XXV/1966, penyebaran ajaran komunisme dilarang, dengan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara jika bertujuan mengganti Pancasila sebagai dasar negara.
Hukum Keluarga dan PKI
PKI, yang aktif pada 1945–1965, tidak secara eksplisit menerapkan hukum keluarga komunis karena Indonesia belum menjadi negara komunis. Namun, PKI mendukung:
- Kesetaraan Gender: Organisasi seperti Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) mempromosikan hak perempuan, termasuk dalam perkawinan dan pekerjaan.
- Reformasi Agraria: Meskipun lebih terkait hukum tanah, reformasi ini bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi yang memengaruhi keluarga petani.
- Pendidikan Massal: PKI mendorong pendidikan untuk semua, yang sejalan dengan kolektivisasi pendidikan dalam komunisme.
Namun, pengaruh PKI dalam hukum keluarga terbatas karena dominasi hukum adat dan agama. Setelah 1965, narasi Orde Baru menggambarkan komunisme sebagai ancaman terhadap nilai-nilai keluarga tradisional, memperkuat stigma terhadap ideologi ini.
Hukum Keluarga Indonesia Pasca-1965
Pada era Orde Baru, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan sebagai kompromi antara kelompok Islam, perempuan, dan pemerintah, menegaskan nilai-nilai Pancasila dan agama. Modernisasi hukum keluarga ini berhasil menekan poligami, perceraian, dan mengatur perkawinan beda agama, yang bertentangan dengan pendekatan komunis yang menolak agama.
Tantangan dan Kritik terhadap Hukum Keluarga Komunis
- Ketidaksesuaian Budaya:
- Pendekatan komunis sering dianggap asing di masyarakat dengan nilai-nilai agama dan adat kuat, seperti di Indonesia.
- Kolektivisasi pengasuhan dan perkawinan bebas ditolak karena melemahkan ikatan keluarga.
- Kontrol Negara Berlebihan:
- Di Uni Soviet dan Tiongkok, negara menggantikan keluarga sebagai pusat otoritas, membatasi kebebasan individu.
- Kebijakan seperti larangan warisan atau perkawinan bebas sering memicu instabilitas sosial.
- Implementasi Tidak Konsisten:
- Banyak negara komunis, seperti Tiongkok pasca-Mao, kembali ke unsur-unsur kapitalis, termasuk kepemilikan pribadi, yang melemahkan prinsip hukum keluarga komunis.
- Kuba dan Vietnam menghadapi keterbatasan ekonomi yang menghambat kolektivisasi penuh.
- Stigma di Indonesia:
- Komunisme dianggap bertentangan dengan Pancasila, terutama asas Ketuhanan Yang Maha Esa, membuat hukum keluarga komunis tidak relevan di Indonesia.
- Narasi Orde Baru tentang PKI sebagai ancaman memperkuat penolakan terhadap ideologi ini, termasuk dalam konteks keluarga.
Keunggulan dan Kelemahan Hukum Keluarga Komunis
Keunggulan
- Kesetaraan Gender: Mendorong perempuan berpartisipasi dalam ekonomi dan politik, mengurangi subordinasi domestik.
- Akses Universal: Kolektivisasi pengasuhan dan pendidikan meningkatkan akses bagi kelompok miskin.
- Penghapusan Ketimpangan: Penolakan warisan dan harta pribadi bertujuan mengurangi kesenjangan kelas.
Kelemahan
- Resistensi Sosial: Pendekatan radikal sering ditolak oleh masyarakat tradisional.
- Krisis Keluarga: Perkawinan bebas dan kolektivisasi memicu perceraian massal dan anak terlantar.
- Kontrol Negara: Otonomi keluarga digantikan oleh dominasi negara, bertentangan dengan tujuan kebebasan.
- Keterbatasan Praktis: Kolektivisasi sulit diterapkan tanpa sumber daya ekonomi yang memadai.
Relevansi di Indonesia Hingga 2025
Di Indonesia, hukum keluarga komunis tidak memiliki relevansi hukum atau praktis karena:
- Larangan Hukum: UU No. 27 Tahun 1999 dan TAP MPRS No. XXV/1966 melarang penyebaran komunisme, termasuk dalam konteks hukum keluarga.
- Dominasi Nilai Agama dan Adat: Hukum keluarga Indonesia berakar pada agama dan adat, yang bertentangan dengan pendekatan sekuler komunis.
- Modernisasi Hukum Keluarga: UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur perkawinan, warisan, dan pengasuhan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, meniadakan kebutuhan akan pendekatan komunis.
- Stigma Sosial: Persepsi negatif terhadap komunisme, yang diperkuat oleh narasi Orde Baru, membuat ideologi ini tidak diterima masyarakat.
Namun, beberapa prinsip komunis, seperti kesetaraan gender, secara tidak langsung tercermin dalam reformasi hukum keluarga Indonesia, misalnya melalui pengakuan hak setara suami-istri dalam UU No. 1 Tahun 1974. Meski demikian, pendekatan ini berbasis nilai agama dan Pancasila, bukan ideologi komunis.
Kesimpulan
Paham komunis menawarkan pendekatan radikal terhadap hukum keluarga dengan menekankan kesetaraan gender, kolektivisasi tanggung jawab rumah tangga, dan penghapusan harta pribadi untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Implementasinya di Uni Soviet, Tiongkok, dan Kuba menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kesetaraan gender dan akses pendidikan, tetapi juga menghadapi resistensi budaya, krisis sosial, dan kontrol negara yang berlebihan. Di Indonesia, hukum keluarga komunis tidak relevan karena larangan hukum, dominasi nilai agama dan adat, serta stigma sosial terhadap komunisme. Hukum keluarga Indonesia, yang diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974, mengedepankan nilai-nilai Pancasila, agama, dan konsensus, yang lebih sesuai dengan konteks budaya dan sosial masyarakat. Meskipun beberapa prinsip seperti kesetaraan gender memiliki kesamaan dengan tujuan komunis, pendekatan Indonesia tetap berakar pada identitas nasional, menjadikan hukum keluarga komunis hanya relevan sebagai studi akademik, bukan praktik hukum. Hingga 2025, hukum keluarga Indonesia akan terus berkembang dalam kerangka Pancasila, menjaga harmoni keluarga sebagai pilar masyarakat tanpa pengaruh ideologi komunis.
BACA JUGA: Panduan Lengkap Travelling ke Sao Tome dan Principe: Menjelajahi Galapagos Afrika